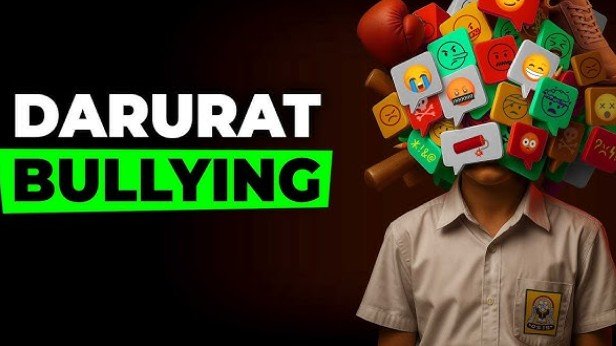*Catatan Muh. Minor, S.Pd (Jurnalis Kampung)
Di tengah maraknya kampanye pendidikan karakter, literasi digital, dan penguatan kesehatan mental, tragedi ini seolah menampar wajah negara, seberapa serius kita sebenarnya dalam memahami, mencegah, dan menindak perundungan yang nyata-nyata sudah merupakan ancaman bagi generasi muda.
Peningkatan kasus perundungan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan bahwa fenomena ini bukan lagi insiden sosial yang bersifat individual, melainkan masalah struktural yang mengakar dalam ekosistem pendidikan dan kehidupan anak.
Data dari KemenPPPA melalui SIMFONI-PPA mencatat hingga 2025 telah terjadi 25.395 kasus kekerasan, termasuk perundungan, dengan mayoritas korban adalah perempuan. Sekolah yang seharusnya menjadi ruang aman justru menjadi salah satu lokasi kejadian tertinggi selain rumah tangga dan fasilitas umum. Bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi adalah psikis, diikuti fisik dan seksual, menandakan bahwa luka yang ditimbulkan tidak selalu kasat mata, tapi tetap berpotensi menghancurkan keutuhan mental korban. Data KPAI memperkuat gambaran kelam tersebut. Pada 2023 tercatat 1.478 kasus bullying secara nasional, meningkat tajam dari hanya 266 kasus pada 2022.
Bahkan, laporan lain menunjukkan sekitar 3.800 kasus perundungan terjadi sepanjang tahun, hampir separuhnya di lingkungan pendidikan, yang mengindikasikan bahwa sekolah belum berfungsi sebagai pelindung yang efektif bagi anak-anak.
Angka-angka ini hampir pasti belum mencerminkan situasi sebenarnya karena banyak kasus yang tidak dilaporkan akibat rasa takut, malu, atau tidak percaya pada mekanisme pelaporan. Fakta-fakta ini menegaskan bahwa Indonesia tengah menghadapi krisis sosial yang meluas. Perundungan telah menjadi epidemi tersembunyi yang merusak generasi sejak usia dini.
Jika hal itu terus dibiarkan, maka kekhawatiran akan terjadinya Indonesia cemas sesungguhnya punya pembenaran yang kuat. Kenaikan kasus yang konsisten itu tidak bisa dilepaskan dari cara perundungan beroperasi dalam dinamika sosial anak dan remaja.
Seminar-seminar anti-bullying yang gencar digelar di sekolah dan kampus seakan tak pernah benar-benar menyentuh akar masalah. Para pelaku perundungan toh masih merasa aman karena tahu bahwa konsekuensi terburuk hanyalah permintaan maaf yang dibacakan setelah segalanya terlambat.
Mirip yang dipertontonkan oleh para kriminal dan badut politik yang semakin sering jadi berita di layar gawai dan televisi. Seolah semua selesai dengan sebaris penyesalan, tanpa pernah terlintas dalam benak mereka bahwa luka yang ditinggalkan pada korban akan menetap seumur hidup, membekas dalam bentuk trauma psikologis yang sulit disembuhkan, bahkan dalam kasus-kasus tertentu berujung pada hilangnya nyawa. Yang lebih menyedihkan, masyarakat kita masih sering gagal memahami dinamika psikologis yang dialami korban.
Alih-alih memberikan empati, tidak sedikit yang justru menyalahkan mereka, mengapa tidak melawan, mengapa tidak melapor, atau bahkan dalam kasus kekerasan seksual, menyalahkan pakaian korban. Cara pandang seperti ini tidak hanya keliru, tetapi juga berbahaya karena memperparah rasa bersalah dan keterasingan yang dirasakan korban. Dalam ilmu psikologi, respons terhadap tekanan ekstrem tidak selalu berbentuk perlawanan. Setidaknya ada tiga reaksi umum yang dikenal, freeze ketika tubuh dan pikiran membeku tidak mampu bereaksi, flight ketika korban memilih menghindar untuk menyelamatkan diri, dan fight ketika ia berusaha melawan. Tiga respons ini bersifat alamiah dan berada di luar kendali kesadaran penuh. Artinya, tidak setiap korban memiliki kapasitas atau keberanian untuk melawan, dan kegagalannya bertahan bukanlah bukti kelemahan, melainkan refleksi dari tekanan psikologis yang terlalu berat untuk ditanggung sendirian.
Di balik setiap tragedi perundungan yang berujung fatal, selalu ada satu pola berulang, negara hadir terlalu terlambat atau bahkan sama sekali tidak hadir. Sekolah, sebagai lingkungan pertama tempat anak belajar tentang nilai dan empati, sering kali justru menjadi ruang yang membiarkan kekerasan psikologis tumbuh subur. Laporan korban kerap diabaikan, pelaku dilindungi atas nama baik institusi, dan penyelesaian kasus kerap berakhir dengan damai yang sejatinya tidak pernah menyembuhkan luka. Aparat penegak hukum pun tidak jarang memandang enteng perundungan, kecuali jika sudah viral atau menelan korban jiwa.
Di balik semua ini, terdapat relasi kuasa yang timpang, pelaku kerap berasal dari keluarga pejabat, pengusaha, atau tokoh berpengaruh, sehingga kasusnya diredam demi reputasi. Hasilnya, pesan yang tertanam di benak pelaku sangat jelas, mereka bisa lolos dari konsekuensi. Dan pesan itu pula yang membuat siklus perundungan terus berulang dari generasi ke generasi.
Di sisi lain, masyarakat dan individu harus membekali diri dengan daya tahan psikologis dan kekuatan moral untuk menghadapi realitas yang tidak selalu adil itu.
Dus, Sikap pendidik dan kepala pendidik sendiri, malah ikut mengintimidasi kalangan pelajar, agar aktifitas selama anak belajar di sekolah tidak diketahui orangtua dan wali siswa.
Hal ini mencerminkan bahwa jatidiri pendidik telah hilang ditelan zaman. Pendidik layak penguasa dan pemimpin perusahaan, yang hanya mengejar predikat dan keteneran nama dari sebuah penghargaan sebagai sekolah unggulan.
Padahal guru yang tidak hanya agen “transfer of knowledge” atau penyaluran ilmu pengetahuan, tapi pembentukan akhlak, kepribadian, dan karakter siswa secara menyeluruh. Guru juga bertugas membimbing siswa dalam mengembangkan keterampilan sosial, emosional, dan spiritual, serta menjadi teladan yang baik.
Termasuk, menjadi fasilitator, pembimbing, agen perubahan, dan pemimpin (leader) dalam proses pendidikan.-*